A. PENDAHULUAN
Latar
Belakang
Ajaran
Islam yang kristalnya berupa al qur’an dan as Sunnah diyakini pemeluknya dapat
mengantisipasi segala kemungkinan yang timbul pada suatu zaman. Islam itu satu,
tapi realitas mengatakan bahwa Islam itu beragam. Misalnya, ada komunitas yang
menampilkan Islam dengan pemerintahan kerajaan, adapula yang senang
pemerintahan republik, bahkan ada juga yang ingin kembali menggunakan sistem
kekhalifahan. Ada yang sangat terikat dengan teks al Qur’an dan al Hadits dalam
memahami hukum Islam, ada pula yang longgar melihat konteks nash tersebut.
Hukum
Islam dari masa ke masa mulai zaman Rasulullah SAW sampai periode sekarang
telah mengalami perkembangan yang begitu signifikan. Lihat saja, pada masa
Rasul, dalam menyelesaikan masalah hukum, para umat bisa langsung menanyakannya
kepada beliau dan dalam menjawabnya beliau langsung mendapatkan wahyu dari
Allah SWT. Setelah beliau wafat, selain menggunakan al Qur’an dan al Hadits
sebagai dasar penyelesaian masalah hukum, juga berijma’ jika tidak menemukannya
dalam kedua sumber tersebut. Pada masa tabi’in, kesepakatan dari sahabat dalam
masalah hukum juga menjadi salah satu sumber hukum dalam menjawab persoalan
umat. Begitu juga masa tabi’it tabi’in ijma’ yang terjadi pada kurun waktu
sebelumnya menjadi pertimbangan dan dasar hukum dalam member solusi atas
problem-problem baru yang muncul.
Pada
bahasan kali ini, penulis akan mencoba membahas keadaan dan perkembangan hukum
Islam pada masa tabi’in khususnya pada masa dinasti umayyah yang mempunyai masa
pemerintahan lebih kurang 91 tahun. Mengenai sumber-sumber hukum serta
pemikiran-pemikiran yang timbul dari sekte-sekte yang timbul pada masa ini dan
yang terkait di dalamnya.
B. RUMUSAN MASALAH
Agar
pembahasan tidak melebar terlalu jauh, maka pada makalah ini penulis akan
membatasi bahasan sebagai berikut:
a. Kondisi hukum islam dan perkembangannya
pada masa tabi’in / dinasti Umayyah
b. Sumber-sumber Islam pada waktu itu
c. Pengaruh ahlul Hadits dan ahlur Ra’y, dan
d. Pemikiran hukum Islam Khawarij, Syi’ah dan
Jumhur
C. PEMBAHASAN
1. Kondisi hukum Islam dan perkembangannya
pada masa tabi’in / dinasti Umayyah
Klasifikasi perkembangan hukum islam
(fiqh) pada era tabi’in sebenarnya masih membingungkan banyak pengamat.
Kebingungan itu dapat dipahami dengan munculnya pergolakan-pergolakan yang
muncul berasal pada masa kekhalifahan Utsman dan Ali dan akhirnya memuncak pada
pemerintahan daulah Umayyah yang melahirkan agitasi teologis cukup tajam. Pergolakan-pergolakan
tersebut justru membawa pengaruh besar terhadap perkembangan hukum Islam
sendiri, sehingga mengantarkan pada era kodifikasi dan munculnya para imam
madzhab[1].
Secara umum para tabi’in pada masa ini
mengikuti manhaj (metode, kaidah istidlal) sahabat dalam mencari hukum. Mereka
merujuk pada al Qur’an dan al Hadits dan apabila tidak mendapatkan dari
keduanya, merreka merujuk pada ijtihad sahabat dan baru setelah itu mereka
sendiri berijtiahad sesuai dengan kaidah-kaidah ijtihad para sahabat.
1.1. Penggunaan Rasio
Ada
kecendrungan baru dari beberapa ahli hukum Islam (fuqoha) untuk memandang hukum
sebagai pertimbangan rasionalitas. Mereka tidak saja banyak menggunakan rasio
dalam memahami hukum dan menyikapi persoalan yang muncul, tetapi juga
memprediksikan suatu peristiwa yang belum terjadi dan memberi hukumnya.
Aliran
pemikiran ini dipelopori oleh Ibrahim bin yazid an Nakha’I,seorang
ahli fiqh irak guru Hammad bin Sulaiman yang banyak mewariskan
pemikiran fiqh rasionalis kepada Abu Hanifah.
Aliran ini tidaklah berjalan mulus, tetapi
banyak mendapatkan tanggapan dan tantangan. Reaksi paling keras berasal dari
ulama Hijaz (Madinah) yang menganggap aliran ini telah menyeleweng dari manhaj
sahabat, bahkan berpaling dari ajaran Rasulullah SAW. Dengan munculnya aliran
ini, dianggap telah membuka pintu untuk memasuki suatu krisis pemahaman
keagamaan sebagaimana yang telah menimpa orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ibnu
Syihab Zuhri, seorang ahli Hadits pada waktu itu pernah mengatakan, “sesungguhnya
orang-orang Yahudi dan Nasrani kehilangan ilmu yang mereka miliki ketika mulai
disibukkan dengan pendapat rasio dan pemikiran”[2].
Sufyan bin Uyainah, Ayyub Sahtayani, Abu
Umar, Auza’I dan Sya’bi adalah ulama terkemuka yang paling vokal menolak
gagasan Ibrahim. “Pendapat mereka itu sebenarnya lebih patut dibuang di
toilet”, kata Sya’bi[3].
Namun tidak berarti fragmentasi fiqhiyyah
pada periode ini memasung perkembangan fiqh. Sebab, meskipun muncul beberapa
reaksi agak keras, namun apresiasi terhadap gagasan Ibrahim dan ulama Irak, pro
maupun kontra, sangat terasa.
Dalam beberapa pertemuan dan dialog yang
mereka adakan untuk mendiskusikan berbagai persoalan yang muncul dan di
munculkan, di irak dan Hijaz dapat ditangkap beberapa isyarat yang memungkinkan
kedua belah pihak saling melengkapi, saling mengisi antara satu dengan lainnya.
Ulama Hijaz yang kaya akan Hadits dan fatwa-fatwa sahabat dipaksa menjawab
persoalan yang belum timbul pada masa Nabi SAW dan sahabat. Demikianlah kebiasaan
ulama Irak memprediksikan suatu peristiwa yang belum muncul itu menuntut ulama
Hijaz untuk menggali tujuan moral, illah dan hikmah yang
menjadi tujuan disyariatkan suatu hukum. Sebaliknya ulama Irak juga sering kali
mencabut pendapatkan yang diketahui, setelah melalui berdialog dengan ulama
HIjaz, bertentangan dengan sunnah Nabi SAW[4].
Pada perkembangan berikutnya terjadilah
pembaharuan, pluralisme dan heterogenitas pemikiran baik di Irak ataupun Hijaz
sendiri yang sangat membantu memperkaya tsarwah fiqhiyyah.
1.2. Meluasnya Ruang Ikhtilaf
Konsekuensi lain dari kontroversialisme
pemahaman fiqh tadi adalah meluasnya ruang ikhtilaf pada periode ini. Dr. Thaha
Jabir dalam bukunya”Adabul Ikhtilaf Fil Islam” menyebutkan bahwa
benih-benih meluasnya ikhtilaf itu sebanarnya telah tumbuh pada masa
pemerintahan khalifah Utsman bin Affan. Utsman adalah khalifah pertama yang
mengizinkan para sahabat untuk meninggalkan madinah dan menyebar ke berbagai
daerah. Lebih dari 300 sahabat pergi ke Basrah dan kufah, sebagian lagi ke
Mesir dan syam[5].
Penyebaran sahabat ke berbagai daerah
tersebut punya pengaruh tersendiri terhadap perkembangan fiqh, paling tidak
perluasan ikhlilaf di kalangan tabi’in. itu dapat dipahami karena masing-masing
daerah memiliki perbedaan situasi, kebiasaan dan kebudayaan, disamping
perbedaan kapasitas pemahaman para ahli fikih dalam mengantisipasi
masalah-masalah yang muncul.
Dalam batas-batas tertentu, karena
perbedaan teori, formulasi, keadaan dan kondisi masyarakat, mereka sering
berbeda dalam satu masalah yang sama. Namun persoalannya tidak sampai di situ,
pergolakan-pergolakn politik sejak terbunuhnya Utsman, pindahnya markas
kakhalifahan ke Kufah kemudian ke Syam dan berbagai konfrontasi yang banyak
memakan korban jiwa, juga faktor yang harus disebut dari meluasnya ikhtilaf
pada periode ini. Ikhtilaf ini semakin melebar sekaligus meruncing ketika
konfrontasi politik antara Ali dan Muawiyyah dan penyelewengan daulah Umayyah
menimbulkan berbagai aliran dan sekte. Pada saat itu muncul aliran Syi’ah,
Khawarij, Jahmiyyah, Mu’tazilah dan lain sebagainya.
2. Sumber-sumber
hukum Islam
Sumber-sumber tasyri’ pada masa ini ada
empat, yaitu Al Qur’an, As Sunnah, Al ijma’ dan Al Ijtihad dengan jalan Al
Qiyas atau dengan salah satu metode untuk Istimbat hukum. Seorang mufti bila
dimintai fatwa terhadap suatu permasalahan dan dia menemukan nash dalam Al
Qur’an atau As Sunnnah yang menunjukan hukum atas persoalan tersebut, maka ia
akan berpegang terhadap nash tersebut dan tidak akan menggunakan dasar yang
lain. Bila dalam suatu kasus, dia tidak menemukan nash untuk mengatasinya
tetapi mendapati ijma’ dari para mujtahid salaf mengenai kasus tersebut, maka
ia pun memeganginya untuk memberikan hukum. Sedang bila dia tidak menemukan
nash tentang kasus itu dan tidak menemukan ijma’ dari hukum yang dimaksud, maka
ia pun berijtihad dan mengistimbatkan hukum dengan jalan yang telah ditunjukan
oleh syara’[6].
3. Pengaruh
ahlul Hadits dan ahlur Ra’y
Dalam catatan sejarah, pusat kekuasaan
politik Islam berpindah-pindah. Madinah di masa Nabi SAW. dan Khulafa al
Rasyidun, Damaskus dimasa dinasti Umayyah, dan Baghdad dimasa dinasti
Abbasiyyah. Penguasa dinasti Umayyah kecuali Umar bin Abdul Aziz,
kelihatannya kurang memperhatikan perkembangan pemikiran keagamaan. Mereka
lebih memusatkan perhatian di bidang politik. Sehingga ketika itu pemikiran
politik dan pemikiran keagamaan berjalan sendiri-sendiri. Penguasa dinasti
Abbasiyyah melihat sikap semacam itu tidaklah tepat. Karena mereka berupaya
agar pemikiran keagamaan dikembangkan bersamaan dengan perkembangan politik dan
filsafat. Para imam madzhab yang tidak mau terlibat dalam urusan pemerintahan
akan dihukum[7].
Dimasa Kulafa al Rasyidun, penguasa adalah
juga alim, menyatu dalam diri khalifah ilmu agama dan kekuasaan. Penguasa
dinasti umayyah kecuali Umar bin Abdul aziz dan penguasa
dinasti Abbasiyyah tidak tahu banyak tentang syari’at Islam dan metode-metode
berijtihad. Urusan agama diserahkan kepada ulama, sedangkan urusan pemerintahan
dan politik dipegang oleh khalifah.
Setelah Islam berdialog dengan masyarakat
luar Arab lebih jauh, peranan akal menjadi penting dalam menjembatani
kesenjangan teks keagamaan dengan persoalan baru. Dalam perkebangan
selanjutnya, dalam pemikiran hukum Islam dikenal kelompok “ahlur Ra’y”,
kelompok yang berani menggunakan akal, yang berkembang di Irak, dan kelompok
“ahlul Hadits”, kelompok yang terikat sekali dengan teks harfiyah Al qur’an dan
Al Hadits, yang berkembang di Hijaz. Keduanya ini muncul bukan karena rekasa
pemerintah, tetapi muncul dari ketulusan hati mereka untuk memberlakukan
syari’at Allah SWT di muka bumi. Perkembangan pemikiran ini berada di luar kontrol
pemerintahan, karena seperti disebutkan di muka bahwa para penguasa
pemerintahan bukanlah orang-orang yang menguasai pengetahuan Agama[8].
3.1. Ahlul Hadits
Dalam masyarakat Islam terdapat kelompok
yang metode pemahamannya terhadap ajaran wahyu amat terikat oleh informasi dari
Nabi SAW. Dengan kata lain ajaran islam itu diperoleh dari al Qur’an dan
petunjuk dari Nabi SAW saja, bukan yang lain. Disamping disebut as Sunnah,
petunjuk dari Nabi SAW juga disebut al Hadits. Karena itu kelompok ini disebut
ahlul Hadits. Mulanya aliran ini timbul di Hijaz, utamanya di Madinah. Karrena
penduduk hijaz lebih banyak mengetahui hadits dan tradisi Rasul disbanding
dengan penduduk di luar Hijaz. Di Madinah sebagai ibukota Islam, beredar Hadits
Nabi SAW yang jauh lebih banyak dan lengkap disbanding dengan daerah lain mana
pun. Semua persoalan hukum dan dan budaya sudah terjawab oleh teks wahyu (al
Qur’an dan al Hadits). Sehingga pada masa itu Hijaz dikenal sebagai pusat
Hadits[9].
Pada masa khulafa al Rasyidun, sumber
hukum Islam adalah apa yang diriwayatkan oleh Nabi (al Qur’an dan al Hadits).
Di masa tabi’in, sumber itu ditambah dengan fatwa sahabat. Ketika dalam
menentukan suatu hukum, tidak ditemukan keduanya, maka ijtihad atau tidak
memberikan fatwa adalah jalannya. Mereka membenci ra’y serta menghindari fatwa
dan istimbat kecuali bila terpaksa dan tidak ada kesempatan untuk mengelak.
Program utama mereka adalah meriwayatkan hadits Nabi Muhammad SAW. di masa
tabi’it tabi’in, sumber hukum islam bertambah lagi, fatwa tabi’in, demikian
seterusnya, generasi mendatang menjadikan fatwa generasi sebelumnya sebagai
sumber hukum Islam.
Masa pemerintahan Umar bin Abdul
Aziz dikenal masa permulaan pembukuan Hadits. Kekhawatiran khalifah
akan semakin tidak terurusnya hadits-hadits Nabi SAW dalam tulisan menggerakkan
hatinya untuk memerintahkan ulama Hadits, seperti Ibn Syihad al Zuhri agar
membukukan hadits. Prestasi penghimpuna Hadits, semenjak dari asal himpun
hingga pemilahan hadits-hadits sahih dari yang tidak sahih, adalah kebanggan
tersendiri dalam menyelamatkan syari’at Islam. Dalam menetapka hukum Islam
mereka mempunyai langkah-langkah sebagai berikut:
1. Bila suatu masalah sudah disebut dalam al
Qur’an maka seorang ulama tidak boleh beranjak kepada yang lain.
2. Bila kandungan ayat al Qur’an itu
menunjukan berbagai kemungkinan maka mereka merujuk hadits yang berbicara hal
yang sama dalam ayat tersebut.
3. Bila ayat al Qur’an tidak menerangkannya,
barulah mereka mencari petunjuk dalam al Hadits, baik yang telah masyhur
dipakai oleh ulama sebelumnya atau yang diriwayatkan oleh penduduk suatu daerah
tertentu.
4. Bila hadits sudah ditemukan maka tidak
boleh mengambil keputusan hukum berdasarkan yurisprudensi/ pemikiran mujtahid.
5. Bila hadits tersebut tidak ditemukan,
keputusan diambil berdasarkan pendapat umum (konsensus). Hasil consensus harus
dippatuhi. Bila masih juga terdapat perbedaan pendapat dalam upaya consensus,
maka keputusan diambil dari pendapat ulama yang paling wara’dan alim[10].
Dengan
demikian, sebenarnya aliran ahlul hadits bukanlah aliran yang sama sekali
menghindari penggunaan akal. Ketawadluan mereka malahirkan sikap kehati-hatian,
sangat mengakui kelemahan akal kendati berkesan tidak berani menggunakan akal
dan sangat mengutamakan penggunaan ajaran wahyu.
3.2. Ahlur Ra’y
Istilah
ahlur ra’y digunakan untuk menyebut kelompok pemikir hukum Islam yang memberi
porsi akal lebih banyak dibanding dengan pemikir lainnya. Bila kelompok lain
dalam menjawab persoalan hukum tampak terikat oleh teks nash (al Qur’an dan al
Hadits) maka kelompok ahlur ra’y tampak tidak terikat, sebaliknya leluasa
menggunakan pendapat akal. Sebenarnya kelompok ini bukanlah berarti kelompok
yang meninggalkan hadits. Mereka juga menggunakan hadits untuk menetapkan hukum.
Hanya mereka dalam melihat kasus penetapan hukum berpendapat bahwa nash syar’I
itu mempunyai tujuan tertentu. Serta nash syar’i secara kumulatif bertujuan
mendatangkan maslahat bagi manusia. Karena banyaknya persoalan
yang merreka hadapi dan terbatasnya jumlah nash, maka mereka berupaya
memikirkan rahasia yang terkandung dibalik nash yang dikenal dengan ta’lil
al ahkam. Sedang kelompok ahlul Hadits lebih memperhatikan penguasaan
hafalan nash dan mengamalkan sesuai dengan bunyi nash tersebut. Pada beberapa
hadits, seperti :
1 .
Setiap 40 ekor kambing zakatnya adalah seekor kambing.
2 .
Zakat fitrah itu satu gantang kurma atau gandum.
Ulama ahlur ra’y memahami nash tersebut
berdasarkan tujuan tasyr’, bukan redaksinya. Sehingga pemilik 40 ekor kambing
tidak harus mengeluarkan zakat berupa seekor kambing, tetapi boleh mengeluarkan
zakat berupa apa saja yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat minimal
seharga satu ekor kambing. Begitu juga dengan zakat fitrah. Bagi mereka zakat
fitrah boleh dibayar dengan kurma atau gandum atau apa saja yang senilai
dengannya. Jadi penyebutan “satu ekor kambing” pada zakat ternak dan “segantang
kurma atau gandum” pada zakat fitrah adalah bukan tujuan tasyri’, tetapi contoh
sarana mewujudkan kesejahtraan umat manusia sebagai tujuan tasyri’. Menurut
ulama ahlul Hadits, pengeluaran zakat hewan ternak berupa satu ekor kambing dan
zakat fitrah berupa segantang kurma atau gandum tidak perlu diganti, takut
tidak sah[11].
4. Pemikiran
hukum Islam Syi’ah, Khawarij, dan Jumhur
Aliran-aliran ini tidak hanya dalam bidang
teologis, tetapi juga berpengaruh dalam sejarah perkembangan Fiqh. Misalnya
menurut Syi’ah, ijma’ dan qiyas bukan sumber hukum dalam Islam. Sebab ijma’
berarti kesepakatan semua mujtahid dari umat Muhammad SAW. setelah kewafatannya
dalam satu masa dan tentang hukum syar’i. padahal mereka tidak mau menerima
pendapat selain dari orang Syi’ah sendiri. Demikian qiyas, sebab hukum hanya
dapat diambil dari al Qur’an, as Sunnah dan para imam-imam mereka yang ma’sum[12].
1. Nikah
mut’ah adalah termasuk sysri’at Islam. Tidak termasuk golongan mereka jika
tidak menghalalkannya.
2. Wanita hanya dapat mewaris benda bergerak
dari mayyit.
3. Waktu shalat hanya ada tiga, yaitu
pertama, Zhuhur dan Ashar (dikerjakan sekaligus pada waktu salah satunya),
kedua maghrib dan Isya’ (dikerjakan sekaligus pada waktu salah satunya), ketiga
shubuh.
Sedangkan khawarij berpendapat bahwa pemimpin
itu untuk umat dan umatlah yang berhak memilih dan memberhentikannya. Diantara
pendapat mereka adalah bahwa perbuatan merupakan bagian dari iman, sehingga
iman saja tidak cukup kalau tidak diamalkan dalam perbuatan[14].
Dalam babakan hukum Islam, kaum ini
mempunyai beberapa pendapat diantaranya:
1. Tidak
ada hukuman rajam bagi wanita pezina mukhsan. Menurut mereka tidak ada dalil
dalam al Qur’an tentang hukman rajam tersebut.
2. Boleh berwasiat untuk ahli waris dan
menolak hadits “tidak ada wasiat untuk ahli waris”. Sebab hadits ini dipandang
bertentangan dengan ayat al Qur’an “diwajibkan atas kamu wasiat bagi kedua
orang tua dan sanak kerabat apabila kamu hendak meninggal”.
3. Thaharah untuk ibadah shalat adalah suci
lahir batin. Kata-kata bohong, kotor, permusuhan dan lain-lain merupakan
prilaku kotor (ma’nawi) yang dapat merusah thaharah.
Pada poin kedua, nampak perbedaan pendapat
dengan jumhur yang menyatakan bahwa ayat tersebut turun sebelum turunnya
ayat-ayat mawaris. Dengan kata lain, menurut jumhur ayat ini tidak berlaku
sebagai legitimasi wasiat untuk ahli waris[15].
D. KESIMPULAN
Dari
uraian yang dapat penulis sampaikan diatas, dapat disimpulkan bahwa secara umum
pada era tabi’in mereka lebih mengikuti manhaj (metode, kaidah istidlal)
sahabat dalam mencari hukum. Mereka merujuk pada al Qur’an dan al Hadits dan
apabila tidak mendapatkan dari keduanya, mereka merujuk pada ijtihad sahabat
dan baru setelah itu mereka sendiri berijtiahad sesuai dengan kaidah-kaidah
ijtihad para sahabat.
Pada
masa ini pula rasio (ra’y) mulai marak digunakan dalam memahami hukum islam.
Ini bermulai ketika seorang Irak Ibrahim bin Yazid an Nakha’I yang hidup pada
waktu itu memandang sulit kiranya jika memahami hukum Islam sesuai dengan teks
harfiyah Qur’an dan Sunnah. Karena Irak adalah daerah yang mempunyai budaya,
adat dan suasana kehidupan yang jauh berbeda dengan HIjaz yang merupakan bumi
Nabi dan Hadits.Meski awalnya mendapatkan tentangan yang cukup keras dari kaum
Hijaz, tapi pada periode berikutnya aliran ini akhirnya mendapatkan apresiasi
dari banyak kalangan.
Pada
masa dinasti Umayyah, para penguasanya, kecuali Umar bin Abdul Aziz, lebih
memfokuskan pada bidang politik serta masalah keagamaan diserahkan pada ulama
setempat. Makanya masa ini lebih terkesan Negara adalah urusan penguasa dan
Agama adalah urusan non penguasa. Dalam istilah lain dikatakan zakat bukanlah
urusan pemerintah, tapi urusan agama. Zakat yang ada ikut campur Negara
dianggap tidak sah.
E. PENUTUP
“Tiada
gading yang tak retak”, mungkin itulah kata-kata yang pas jika tulisan ini
dibaca. Maka saran dan kritik yang konstruktif sangat penulis harapkan dari
pembaca. Semoga manfaat dan berkah “always” tercurahkan kepada siapapun yang
telah meluangkan waktunya untuk membaca tulisan ini. Amin.
F. DAFTAR PUSTAKA
A. Sirry ,Mun’im, Sejarah Fiqih
Islam: Sebuah Pengantar,1995, Surabaya: Risalah Gusti.
Jabir
Fayyadh, Thaha, ‘Ulwani, Adabul Ikhtilaf Fil Islam,
Khallaf,
Abdul Wahhab, Ikhtisar Sejarah Hukum Islam, 1985, Yogyakarta:
Dua Dimensi.
Qoyyim,
Ibnul,al Jauziy, I’lamul Muqi’in, Jilid 1,
Zuhri, Muh, Hukum Islam dalam Lintasan
Sejarah, 1996, Jakarta: PT RajaGrafindo persada.
[1] Mun’im A. Sirry, Sejarah Fiqih Islam: Sebuah
Pengantar, Risalah Gusti:Surabaya, hlm. 49.
[2] Ibnul Qoyyim al Jauziy, I’lamul Muqi’in, Jilid
1, hlm. 74.
[3] Mun’im A. Sirry, op.cit. hlm.50.
[4] Mun’im A. Sirry, Ibid, hlm. 51
[5] Dr. Thaha Jabir Fayyadh ‘Ulwani, Adabul Ikhtilaf Fil
Islam, hlm.21.
[6] Abdul Wahhab Khallaf, Ikhtisar sejarah Hukum
Islam, hlm. 51.
[7] Dr. Muh. Zuhri, Hukum Islam dalam Lintatasan
Sejarah, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, hlm.65.
[8] Ibid, hlm.66.
[9] Ibid, hlm.67
[10] Ibid, hlm.68.
[11] Ibid, hlm.70.
[12] Mun’im A. Sirry, op.cit, hlm. 54
[13] Dr. Muh. Zuhri, Op.cit. hlm.62
[14] Op.Cit, hlm. 54
[15] Ibid, hlm. 57.
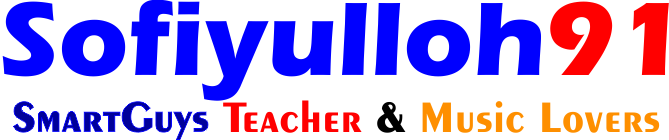
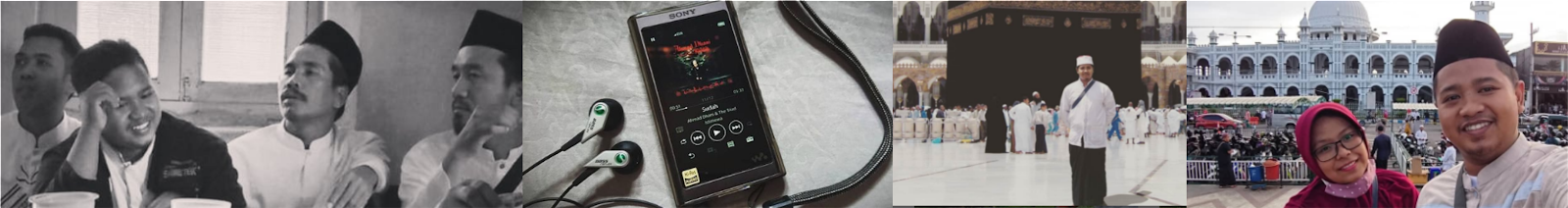
Posting Komentar
Komentar Anda tidak merubah apapun...!